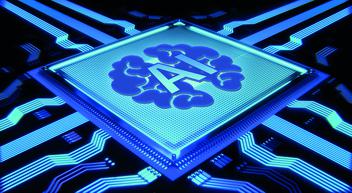KNews.id – Jakarta – Kecerdasan buatan (AI) memang tidak bisa dielakkan kecanggihannya. Sering kali video yang berasal dari teknologi ini berlalu-lalang di media sosial. Terkadang pula video yang dihasilkan adalah video sejarah mengisahkan legenda, perpecahan kerajaan, bahkan fakta yang belum diketahui banyak orang.
Dalam sesi “AI for Better Cultural and Traditional Awareness” pada AiDEA Weeks 2025, dibahas bagaimana AI menjadi peramban untuk memvisualkan dan menjelaskan sebuah cerita sejarah. Mulai dari awal konflik hingga penggambaran dan produksi di baliknya.
Salah satu pembicara dari Founder Lotus dari Curaweda Tech, Azhar Muhammad Fuad, menyoroti manfaat AI yang potensial atau disebut “Blue Ocean” untuk digunakan di sektor sejarah budaya. “AI tiba-tiba banyak, momen yang pas untuk seluruh kalangan bisa mengakses dan mengetahui seberapa capable AI,” tutur Azhar, Jumat (14/11/2025) di Jakarta.
Dalam produksi sebuah karya melalui kecerdasan buatan, Azhar kerap menemukan beberapa hal yang tidak dipertanggung jawabkan. Berdasarkan kasus tersebut, ia dan founder Curaweda membicarakan konsep etika AI yang bukan hanya grafik gambar tetapi fakta yang sudah terjadi sebelumnya.
“Melihat opportunity tadi, kami di Curaweda ngobrol soal konsep etika AI, di mana bukan hanya ngomong ‘oh ini ada dasarnya’,” ia menjelaskan.
Cerita lain datang dari Founder dan Akademisi AI Nusantara, Gustav Anandhita, saat ia harus mempertanggung jawabkan konten yang dibuatnya. Kala itu AI belum kompleks seperti saat ini. Namun konten buatannya disorot media nasional seolah visual yang dihasilkan sesuai dan mirip dengan dulunya.
“Waktu itu AI masih berkembang, jadi hasilnya random. Tapi dibuat oleh media nasional, seolah-olah memang itu adalah sesuatu yang real, dari situ jadi tanggung jawab moral saya,” ungkap Gustav. Gustav kemudian memutuskan untuk mengajukan proposal penelitian teknologi AI untuk memvisualkan sejarah. Mulai dari sejarawan, budayawan, hingga spiritualitas mengomentari karya yang ingin dirancangnya.
“Kami ajukan proposal, biar kita balik ke (cerita) sebenarnya. Ketika divisualkan, itu seperti apa, preferensinya menuju ke mana,” ujarnya.
Produksi Visual Sejarah Tidak Lepas dari Data
Untuk membuat konten visual, terutama sejarah, Azhar menyoroti tantangan utama berasal dari resistensi internal sejarah. Menurutnya, setiap orang memiliki versi sejarahnya masing-masing sehingga menuntutnya untuk literasi dan verifikasi dari pihak terkait.
“Poinnya itu memang bukan di teknologi, tapi di akurasi sejarahnya,” tegas Azhar. Proses produksi bukan sekadar teknis membuat prompt dan membiarkan AI bekerja sendiri, tetapi Azhar melibatkan kesepakatan dengan pihak terkait sejarah yang diangkatnya.
“Sejarahnya itu harus dikawal, harus ditunjuk oleh pihak tersebut, nantinya kita sepakatkan bentuk cerita seperti apa, terus scene-nya gimana, itu kesepakatan di sana yang dibangun dalam bentuk konsep heroik,” tuturnya.
Sementara Gustav menyebut resistensi harus digali hingga mendapatkan informasi valid. Mulai dari barang yang digunakan, warna tiap objek hingga motif kain. Hal ini harus dilatih AI untuk memastikan data sesuai atas izin pemilik.
“Kalau kita melatih AI pastikan datanya atas izin pemilik atau orang yang kepentingan. Kita bekerja sama dengan budayawan untuk memastikan pola yang dihasilkan AI memiliki value, masih memiliki karakteristik,” ungkapnya.
Proses Pra Produksi Makan Waktu
Azhar mengakui penggunaan AI dalam produksi visual sejarah memang kerap menimbulkan sensitivitas, terutama kekhawatiran teknologi dapat menggeser pekerjaan tertentu. Meski demikian, ia menegaskan Curaweda tidak menggantikan proses produksi, melainkan mengubah cara kerja agar lebih efisien. Proses produksi konten AI membutuhkan waktu 20 hari, sedangkan waktu pra-produksi memakan waktu 3 bulan.
“Praproduksi itu kita datang langsung, terus diskusi sama sejarawan, dikepung sama arkeolog, dikepung sama budayawan. Kalau buat micro movie 10 menit, kita buat dalam waktu 20 hari, tapi pra-produksinya 3 bulan,” Azhar memaparkan. Salah satu contoh diceritakan Azhar adalah proyek rekonstruksi Gua Harimau di Sumatera Selatan, di mana seluruh visual dibuat berdasarkan temuan ilmiah.
Azhar juga mengungkapkan karya Curaweda tidak pernah dirilis di media sosial atau YouTube. Semua hasil karya Curaweda ditayangkan eksklusif di museum atau situs sejarah agar pemaknaan konteks cerita tetap terjaga. “Kita tidak pernah muncul, baik di media sosial, apalagi di YouTube. Jadi yang di luar sana (media sosial) itu bukan Curaweda, yang kami buat pasti ada di tempat-tempat sejarah budaya,” tegasnya.
AI Mempertemukan Beberapa Profesi dan Saling Berkolaborasi
Gustav Anandhita menekankan salah satu kekuatan besar AI dalam ranah budaya adalah kemampuan mempertemukan disiplin ilmu dalam ruang kerja yang sama. Baginya, AI bukan sekadar alat visualisasi, tetapi perangkat kolaborasi.
“Menurut saya, AI itu justru membuka adanya kolaborasi berbagi dunia. Karena AI itu kayak semacam translator dari berbagai pengetahuan,” tutur Gustav. Ia mencontohkan proyek rekonstruksi Arca Majapahit yang mempertemukan arsitek, ahli komputer, tim Balai Konservasi Peninggalan (BKP), sejarawan, akreolog, hingga budayawan.
“Contoh di proyek Arca Majapahit. Saya tidak menyangka arsitek, ilmu komputer, BKP, sejarawan, arkeolog, budayawan, ngomongin hal yang sama, yang dulu mungkin gak bisa kita bayangkan,” imbuhnya, menceritakan.
Gustav mengaku sempat terjebak dalam persepsi modern tentang proporsi tubuh manusia sebelumnya. Namun kini ia berpegang dengan sumber resmi dan penelitian yang menunjukkan proporsi nenek moyang besar dan kekar.
Hasil visual fisik dari AI bukan untuk membuat tampak berwibawa atau cantik. Namun hasil tersebut mengikuti data dan ilustrasi resmi yang dipublikasi kementerian.